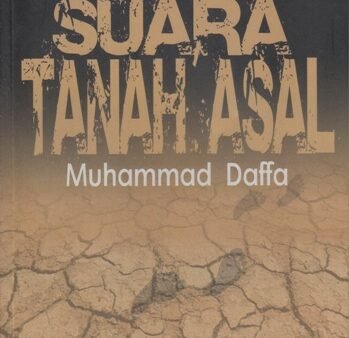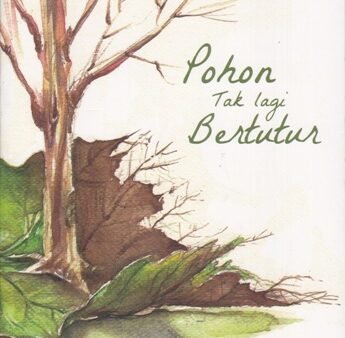Data buku kumpulan puisi
Judul : Air Tulang Ibu (antologi 2 bahasa, Indonesia-Inggris)
Penulis : Zelfeni Wimra
Penerbit : Pusakata Publising, Padang.
Cetakan : I, Oktober 2012
Tebal : 103 halaman (70 puisi)
ISBN : 978-602-99686-6-8
Penyunting : Sunlie Thomas Alexander
Foto Sampul : Agung P.
Desain Sampul : Fatris MF, Ilhami el-Yunusiy
Penata Isi : Alaik
Translator ke bahasa Inggris : Ali Akbar, Benny Sumarna,
Heru Joni Putra, Nofel Nofiadridan Fitra Yanti Zelfeni
Air Tulang Ibu terdiri dari 3 bagian, Periode Air(17 puisi), Periode Tulang (35 puisi) dan Periode Ibu (18 puisi).
Beberapa pilihan puisi Zelfeni Wimra dalam Air Tulang Ibu
obat ibu
“melihat anak pulang: obat penenang segala kejang,”
2008
pecah di gugus nisan
i
kisah kita di rahim dapur
umpama tungku ditinggal api
menyerahkan rindu pada kerlingan bara
pada decak gelegak air pemanas kopi
ii
cengkrama kita di ruang tamu
umpama luka ditinggal belati
membiru
ketika amin doaku
pecah di gugus nisan
lahat yang dingin
menjelma ranjang pengantin
padang, 1999
tempat menahan airmata
sementara usia memamah nyawa
kita coba jadi orang-orang riang
terbahak di rumpun lobak sawi
pada kepal nasi di licin daun pisang
minyak sambal dan butir-butir rimbang
kita santap jerih mencangkul bumi
ndeh, kenangan itu, kini berkali-kali
mengusik perantauanku
mencangkungi ubun-ubun
menumbuk sunyi tempurung kepala
kiranya telah sampai kabarnya padamu
di sinilah, pada liang tulang paling dingin
antara selaput gendang dan retina
aku telah terbiasa menahan airmata
2006-2011
hulu dan hilir
orang merantau kita katakan berangkat ke hilir
perantau pulang kita sebut balik ke hulu
pengantin wanita, bayi lahir, dan orang mati
kita anggap melingkari putaran
yang berakhir di pelabuhan matahari
kita sendiri sedang apa?
berjuntai-juntai diguyur arus
beruntung ada ikan yang suka, lalu memakan kita
atau ada peternak sapi datang membawa sabit dan karung
baru boleh dikatakan nasib kita sempurna sebagai rumput
melumatkan diri ke dalam usus dan anus ternak
kalau tidak demikian,
selamanya kita di tepi sungai ini
menggigit lidah, berputih mata
orang-orang terus merantau
orang-orang terus pulang
dan anak pinus yang dulu berlindung di balik rimbun daun kita
telah besar menjulang
2011
serangga dan pujangga
serangga:
purnama memperdayaku
tapi sayapku tidak berdaya
mengayuh udara lebih tinggi dari pucuk kelapa
itulah sebab, mengapa aku tersesat ke lampu-lampu di rumahmu
pujangga:
aku selalu digoda cinta
tapi syairku tidak kuasa
melompat lebih jauh dari pekarangan seberang jendela
itulah sebab, mengapa cintaku terjebak di sajak ini saja
2011
ladang tulang ibu
“mari menyemai daging di perutku
aku punya tujuh lapis kulit, selaut darah,
dan sebidang ladang tempat menanam tulang,”
pinta ibu pada bapak
api menyala di patahan sumsumnya
ibu berdarah
aku pun tumbuh di ladang ibu
bersama hujan yang dipiuh bapak
dari kulit ari badannya
dari perih dagingnya
“lapis kulit, kepal daging,
dan gemulung uratmu
berasal dari luka,”
padangpanjang, desember 2000
puisi yang berlinang
tenggelamkan matamu
dalam air puisiku
lebarkan senyum
sebagaimana bunga melepas embun
semua tangis akan tuntas sendiri
meski sebagian tersimpan untukmu
pembasuh retina, agar kau tetap
bisa memahami cahaya
bukankah langit adalah puisi yang selalu berlinang
karenanyalah laut menjadi dalam
jika hari tidak hujan, setiap pagi,
ia tarikan embun penimbun bumi
meski tidak lama, hanya menjelang matahari kembali
membawanya pulang
pauh, 2001
kaba tanah mati
air daki tubuh-tubuh pirau
melinangi ladang-ladang
bertanah dingin
ingin kujelaskan desah gerimis
memburai dari mata putih penghuninya;
bangkai ibu tinggal kulit pembalut tulang
membanting berjinjing sepi
membilang gantungan untung
bak laba-laba:
“perkelahian ini, kekasih, tidak membutuhkan jurus-jurus
cukup dengan merangkai jejaring dari getah tinja sendiri,
lalu memajangnya (kira-kira) di mana mangsa melintas,”
atau merangkak bak serangkak
menyeret punggung perih; menghiliri nasib
di tanah yang juga asin
ingin pula kukisahkan
pori-pori lengan peneruka
padamu barangkali
serta luka kecil yang bersilangan di bahunya,
membabat belantara
tempat –berkurun kemudian— kita menanam kota
padang, 2007
sehamparan tanah ibu
dada di cuaca penghabisan
bulan penat tak terurus
aku dengar riuh tepuk tangan
ibu kurus dibalut gigil
terguling di beranda gosong
mengurut kekalahan
jangkirnya digusur tungkai-tungkai sore
tanpa alasan berselisih
melindang keliar jejak orang-orang pindah
merangkul rumah ke tepi luka hari
bersilih salam pamit
langit tak bermusim menyuling mata hujan jadi riam
sesendu lambai anak-anak batang kampar
menghilirkan remah gergaji ke muara lengang
sementara ini kampung hanya sarang semut
menara tanah yang segera rubuh
“apa yang kita dapat dari perpisahan?”
selain kesendirian, cuma gelimang lumpur rindu
ladang-ladang lumat diparut beling tahta
deret catatan harian rumah tanpa halaman
hiruk-pikuk tak berkesudahan
menggelinjang pada partitur tanah yang lantak
rengek-ratap ganti rugi bagai lengking sirene
di gerbang pekan hilang sejarah
hingga aku lupa usia beringsut ke pinggir nisan
tidak mengerti justru kota yang menyubur
serupa gagang peria di persemaian
“coba kaparkan badan
picingkan mata
bukan hanya aku
para penakluk hutan melayu juga berkubur di sini
di sisi batang mangilang
alamat doa bila kelak kau berziarah,”
ngiang yang panjang
seakan ibu menjangkau bahuku
ajari aku mengapung
menghulu ke muara takus
menakik dupa yang raib di rimba bukitbarisan
dalam kabut aku tumbuh
bagai gandarokam, berseteru dengan duri semambu
merendang angka-angka yang jumpalitan
berebut selara kenangan
waktu malah memisau
meruncing sembilu bakau tanjung pauh
aku tumbang tanpa hikayat
mengarung gerenek batang samo
segala gagau terbenam, ibu
rumah, taman bunga, dan halaman masjid perempatan aspal
melepuh
di kedalaman angkuh
aku temukan sisa kanak-kanakku
pongang sorak petak umpet
anak lanang menari melagukan barzanji
berlari menakali capung dengan lidi
atau mandi-mandi bersama dedaun
yang diluruhkan angin khatulistiwa
lalu lapuk di ceruk keranda
berlesatan ke seberang jelujur menara tanah
“sejenak pun, tinjaulah
hamparan itu menunggu lentera
penyuluh sobekan rahasia yang menyala di nadimu
menjelang padam, carilah hang tuah, nak!
atau telah kau genapkan diri menjadi malin kundang?”
ke padang-padang melayu, aku ingin berburu, ibu
melanglang panah harapan
tak ada kata pulang
sebelum busur menggeleparkan buruan
tapi bagaimana mencecah onak sunyi
merunut belukar risau?
selalu ranah koto panjang ngangkang di udara
layar tak berhingga memajang bukit berbaris
sungai-sungai kecil berjabat di perut rawa
seketika, cericit burung pemakan buah kayu
meningkahi dingin pagi
padahal, hanya riwayat pahang tiang-tiang listrik
kuyup dipeluk karat
gamang menunjuk langit
rumah sekolah membangkai
getah para menjelma bubur rawa
berbidang sawah gugur
sawit mati muda
membusuk di rusuk kota yang membentang
jeram peradaban
licin waktu tak terjinakkan
aku gembalakan hati
tapi suit jua
serupa pori-pori lengan peneruka
mengeras di hulu cangkul
bertahun menampar sekawanan humus
pada gulungan tali kerbau
di serajut rumput dan onggokan tinja kambing
nasib mereka memilin tak terkemasi
jika sore merah inai meretas langit
burung-burung pemakan buah pulang ke sarang
mereka terseok di pelipis jalan
menggendong sibiran kayu, menanti api
lalu siapa saja boleh jadi tungku
jadi garam atau kuali
di mana perjalanan dididihkan
ndeh oi, berapa kilometer lagi harus kutempuh nyeri
hingga ziarah ini sampai ke puncak?
lidahku meretak pahit, menuang doa ke banjaran nisan
nan luput dari hitungan
tak ada lagi rumah bersendi batu
hanya menara tanah yang telah lama luluh
melunau di hamparan tanah ibu.
2006-2007
peria dan tebu
di atas satu bedeng, kita tanam sepasang tangan petani
sebenarnya kamu juga ingin menolak, bukan?
tapi apa nak dibuat, kita harus julurkan akar-akar kita
kembangkan daun-daun kita
menyerap inti tanah dengan cara masing-masing
tumbuh mesti diteruskan
pada waktunya nanti akan nyata juga
ulat penyuka pahit akan memasukiku dari dalam
dan semut-semut pemburu manis bersarang di ceruk kelopakmu
cara kita menyerap makanan sama
di tanah bedeng yang sama
takdir namanya, yang kemudian membuat
kita berbeda rasa
kita harus betah bersama di bedeng ini
sampai musim panen tiba
perpisahan yang kita rindukan itu akan tiba pula
maka bersiaplah menuju pasar
menerima sakit yang lain
aku akan diracik dan digulai
dan kau diperas sampai ampas
lain kali nanti mungkin akan bertemu lagi
dalam musim yang lebih cair
2011
ubun-ubun bau pisang batu masak
tiba-tiba aku serasa mencium bau pisang batu masak
ketika mendekap ubun-ubunmu
“lihat mataku. ada barisan anak cabe rawit; abu jerami beterbangan;
lender biji cokelat; dan tangkai cangkul dari cabang surian…”
senyummu menukik ke dalam tangisku
sesuatu yang menyenangkan telah meremangkan ubun-ubunmu
tubuhku serasa mengerdil
meronta dalam buaian bayi tujuh bulan
kedipan terakhirmu begitu riang
mengajakku mencandai boneka musang
sebelum gelap, kikis lagi pisang batu masak
dengan ujung sendok teh itu
suapi aku
suapi aku
2010
anak rambut ibu
“ambil sebutir gabah
pilih sehelai uban di antara rambut ibu
gunakan kesat kulit gabah itu untuk mencabutnya,”
“kenapa rambut bisa putih, bu?”
“itu karena perangai waktu,”
aku pun memilih uban ibu
mencabut dan mengumpulkannya
“ibu. sudah. kalau terus dicabut
nanti semua rambut ibu akan terenggut,”
“tidak apa. setiap kali dicabut akan selalu ada anak rambut
tumbuh baru menggantikan,”
“tapi, mengapa anak rambut ibu juga putih?”
“itu karena perangai waktu,”
2002
mata
menyeberang ke ngarai mataku pilihan berlibur paling riang
ajaklah semua keinginanmu, kenangan kerontang kemarau
tinggalkan di bukit pelupuk
aku antar penyeberanganmu dengan sebuah kisah:
ketika suluh adam sudah menyala
tuhan menatapnya, sorotan maha cahaya
memijar bahagia
akan melata sejenis makhluk paripurna
suluh di matanya meliputi jagat raya
meski mereka menjadikan tumpahan darah
sebagai alat pembayar bahagia
tanpa rakit lebih baik. berenang sajalah
biar poriporimu merasakan sendiri geliat riaknya
teruslah mengayuh tubuh
hingga ke hulu jantungku
naiklah. jangan ragu dengan gerakan
yang membuat air melimpah ke tebing wajahku
itu biasa dan akan kujadikan tanda
bahwa seseorang sedang berusaha menyeberangiku
setelah kau sampai, berusahalah untuk tidak tercengang
dan merasa buta, karena di sana ternyata tidak ada cahaya
2009
hujan di tepi kerudung
:fy
duduk di sini. mengajilah
tilawahkan yasin bagi sore yang sebentar lagi pergi
entah kapan kau bisa kembali
membaca ayat-ayat mata yang tiris
dan tangan risaunya
barangkali telah debu
ketika nanti kau ingin meraih jarinya
mengajilah, meski belum ingin
jantungnya mungkin segera berhenti
bacakan surat-surat hujan yang berdesau
saat tangannya menjangkau anak rambut
di tepi kerudungmu
2007
sandal tipis dan anak tangga
sandal itu makin tipis
bila putus jua
bangkainya akan kusimpan
di rusuk anak tangga
tanda kepergian
dan kepulangan
telah mengalih jalan kembali kita
2008
tangan
agar kelak punya kenangan, sebaiknya kita bersalaman
memastikan uap hangat darah masih mengepul ke tapak tangan
sesuatu yang acap meronta itu, masih menggelegak
di persembunyian nyawa
nanti akan kira ceritakan lagi, dalam sebuah perjalanan
ruas tangan kita pernah menyatu
kini, duduklah semeja denganku
pastikan tanganmu sudah bersih
kita hadapi hidangan ini
berkeliaran sepanjang hari
telah mengeringkan rahang
saatnya menyantap pencarian
nanti akan kita ceritakan lagi
dalam sebuah perjamuan, selera kita pernah berpacu
setelah kenyang, apalagi?
kita bersalaman lagi?
o, ditambah seikat pelukan
baik. tapi biarkan aku sedikit menjauh
sebelum kemudian kita sama-sama melabai
nanti akan kita ceritakan lagi, sesuai perjalanan dan perjamuan
kita pernah bersalaman dan berpelukan
2009
narasi nabi yang penangis
1
sejenak ia terkenang mengapa nuh jadi nabi yang penangis
sebuah periode ketika laut kian bangka
tentang ibu yang menanak perahu di matanya
pada reruntuhan dapur
seorang lelaki berkayuh
meraba gemuruh rindu dan uap kubur
anak-anak mereka bergigilan
memandang sisa selimut di tali jemuran
bangkai layang-layang
menakik rumah yang lantak
sawah yang sabak
2
pada dinding ia mengada dalam lukisan anak dan peron licin
menggulung tiket keberangkatan
tanpa pagut doa atau kekasih
angin pelabuhan pastilah dingin
“tapi jangan ucap cemas, ibu
selimut-baju pemberianmu
masih biru dan akan sering aku pakai,”
3
ia gambar rupa bapak, beranda, dan secawan pagi
gurih bulir cengkeh dan gurau anak-anak mengaji
menyapu halaman rumah tinggal
pada tangga tahun, ketika rebab masih mengalun
bapak mandi-mandi di pancuran sepulang menakik mayang nira
nasi kunyit dalam rantang alifbata
meraungi kerak luluk di mata kakinya
malam yang mengekalkan ciuman bini
hanya cahaya togok bersaksi pada serpih dinding bambu
tapi laut telah memakan kayuh
ia lupa. pada relung sebuah jorong
dengung sejarah meluncur di tepian kain sarung
berbilang musim reot mengukur ritus pelarian
sepanjang gelombang
4
ia serahkan hidup ke riak
waktu amat mada bagi harapan tak terakit
hingga keluh dilabuhkan ibu
tersisa satu tanya: perahu yang membawamu
ke pantai ini, kandas di mana, bapak?
5
malam terus mengecipak pada bilah kayuh
tapi laut tetaplah debur yang bangkang
melonjak-lonjak serupa lebah digelimang kenang
jorong yang sempat ia sayat
tinggal kedip kunang di daratan jauh
6
ialah seorang jantan pelaut
di lapak-lapak sore, mencincang jejari tangannya
“agar tidak ada lagi lambaian
dan garis menikung yang menjauhkan aku dari pantai,” racaunya
“tapi takdirmu tersirat di situ,” cegat sesuara mirip ibu
tapi jejari itu terlanjur luluh
seperti sore. tergeletak
seperti nuh
ia pun menangis
sungai naniang, 2006
Tentang Zelfeni Wimra
Zelfeni Wimra lahir di Sungai Naniang, 26 Oktober 1979. Menamatkan pendidikan di IAIN Imam Bonjol Padang (S1-2004 dan S2-2011). Menekuni penulisan cerpen, cerita rakyat, cerita anak, drama, novel dan puisi. Diundang menghadiri Mastera, penulisan naskah drama, Bogor, 2010 dan UWRF 2010. Buku cerpennya Pengantin Subuh (LPH, 2009), Yang Menunggu dengan Payung (menunggu terbit) dan Jembatan Dua Kepala (menunggu terbit). Air Tulang Ibu (2012) adalah kumpulan puisinya yang pertama.
Catatan lain
Air Tulang Ibu, semacam buku yang dibuat bolak-balik. 103 halaman berbahasa Indonesia. 103 halaman berbahasa Inggris. Ada 5 (lima) orang translator yang dituliskan juga biodatanya di halaman 102 buku ini. Mereka adalah Ali Akbar (mengalihbahasakan 14 puisi), Benny Sumarna (Benny Kay/Benny S Kolen)-22 puisi, Heru Joni Putra (18 puisi), Nofel Nofiadri (13 puisi) dan Fitra Yanti Zelfeni (2 puisi). Nama translator ditulis tepat di bawah puisi yang diterjemahkan ke bahasa Inggris.
Bunyi halaman persembahan: Buat Amak:/Helmi Wirda /(04/08/1954- 29/08/2010)/menjernihkan mata air doa/puisi-puisiku terasa tiada bertulang.
Dan di halaman terakhir buku ada kata-kata berikut: Saya salut pada/halaman terakhir/setiap buku/Disentuh dan dibuka/hanya sekali/sebelum buku ditutup/kembali.