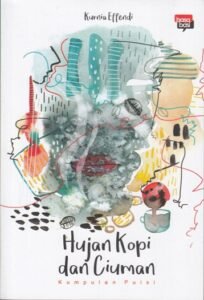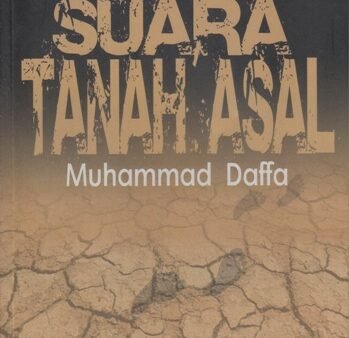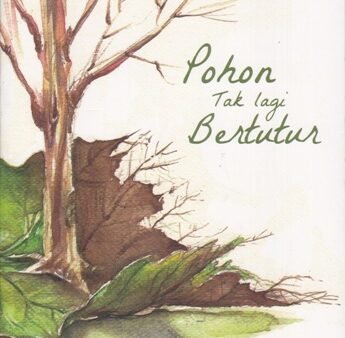Data buku kumpulan puisi
Judul : Hujan Kopi dan Ciuman
Penulis : Kurnia Effendi
Cetakan : I, September 2017
Penerbit : BASABASI, Yogyakarta.
Tebal : 144 halaman (101 puisi)
ISBN : 978-602-6651-40-2
Penyunting : Tia Setiadi
Tata letak : Amalina
Tata isi : Violetta
Pracetak : Kiki
Sepilihan puisi Kurnia Effendi dalam Hujan Kopi dan Ciuman
Tubuh Ibu
Malam memasang jubah sunyi, ketika tubuh Ibu menjelma
rumah dengan banyak kamar. Detik berjatuhan serupa merjan yang
lepas dari ikatan. Bergulir menjauh, merepih bunyi yang tak
sungguh sampai pada telinga.
Seiring gumpalan waktu yang diseret maut,
satu per satu benda-benda dalam tubuh Ibu pamit:
pankreas, ginjal, empedu, hati, paru-paru, batang otak, dan jantung.
Seperti penjaga yang menunaikan tugas, satu demi satu
ruang dalam tubuh Ibu memadamkan lampu.
Gelap itu sampai ketika pagi memercikkan cahaya matahari
Tubuh Ibu bercakap-cakap dengan mesin yang seolah serbatahu
Di ambang pintu, malaikat telah menunggu. Napas yang tersisa pada
serabut kusut di balik dada Ibu mulai dilepas terbang. Dan doa
berenang pada genangan udara, meraih tepi, yang
membatasi antara terjaga dan mati suri.
Kini ruh beringsut dari jemari kaki ke lutut, dari paha ke perut, dari
dada ke rambut. Meninggalkan suhu yang menyusut. Selembut
kasihnya sepanjang tujuh puluh satu tahun, tak terhindar rasa sakit
saat meninggalkan raga tempatnya berdiam. Kernyit sejenak di
antara kedua mata Ibu merupakan isyarat perpisahan.
Aku tak pernah tahu, ke mana ruh itu pergi: utara atau tenggara
Ia menjauh dari tubuh Ibu mungkin dengan rasa pilu yang
dititipkannya kepadaku
Slawi, 2011
Melukis Hujan
Tuhan, ajari aku melukis hujan
Garis basah pada latar akuarel
Titik yang memanjang dari ujung jari-Mu menuju bumi
Setrum cinta yang murni
Bingkai lanskap, batas yang lepas dari perangkap
Cahaya luntur dalam tekstur kelabu
Kasih yang tercurah menanggung hujah
Kanvas ini lumut, seolah hujan mengawali kiamat
Tuhan, kupasang di mana lukisan hujan ini?
Horison leleh menyeduh hasrat manusia
Hanyut harapan ke muara menjelma genangan pikiran
Mengubah anugerah menjadi keluh kesah, rahmat menghimpun
kesumat
Hujan, ajari aku melukis Tuhan
Jakarta, 2014
Lelaki Semburat Matahari
Biarkan sebuah pagi kembali
melewati gelap jalan ini
mengendap dari dasar perigi
dan saat semburat cahaya matahari
terlukis wajahmu pada langit pasi
Kubiarkan engkau lewat jalan ini
menating bilah-bilah puisi
setipis ilalang, selunglai untai jerami
untuk semata menandai
bahwa usiamu terpangkas seruas lagi
Hanya dengan himpunan puisi
pesta itu dirayakan berulang kali
hanya dengan semburat cahaya matahari
lelaki sepertimu percaya pada ujung hari
: sebuah senja yang nyaris abadi
Jakarta, 2009
4 Kwatrin tentang Kopi
1.
Di anjungan yang tak tenang: horison bergelombang
Tampak samar hutan tropis Brazilia di bawah kawanan tipis awan
Akan kukenang pertemuan kita seperti menjalin benang
Sebelum kopi dingin, sebelum hilang seluruh angan
2.
Cahaya membuka pagi dan pagi membuka kamarmu
Separuh malam penghabisan: setelanjang inikah hidup kita?
Dari Jambi ke Lampung, dari dahi ke lambung
Aroma kopi membuka rahasia sehelai demi sehelai
3.
Kedai Jasa Ayah tidur lebih larut malam ini
Kutanggap cerita Helena yang ikal mirip rambutnya
Tanpa musik, tanpa gambar, tanpa syahwat sang pemberani
Tokoh kisah menari lincah di selingkar cangkir kopi kita
4.
Kupesan kopi dengan susu dari penjual bersepeda keliling
Ia menawarkan riwayat hidupnya sebagai hadiah
Saat kubayar dengan uang gaji pertama setelah menganggur lama
Ia membekaliku inspirasi:”Bawalah untuk hari tuamu.”
Jakarta, 2017
9 Haiku tentang Kopi
1.
kasihku: Eva
lingkar pinggang Pringsurat
terkecup hangat
2.
lebar Malabar
paras petani kopi
disekap kabut
3.
secangkir cinta
dalam pekat renjana
memagut Bromo
4.
marilah, Gayo!
setengah hari lagi
dirundung kopi
5.
tamasya mata
sepanjang Mandailing
merenggut hasrat
6.
pertanyaanku:
mengapa di Toraja
kureguk candu?
7.
Bali kembali
terendam didih kopi
di Kintamani
8.
“Ambil sabitmu.
Mari ke Sidikalang.”
Ziarah wangi
9.
terbang arwahku
robusta-arabika
di pangkal jantung
Jakarta, 2017
Purnama
– dari penyair rumah anggit kepada penyair sahaja
Ia berjalan lambat ke barat
Dengan puisi di tangan, di antara kapas-kapas awan
Pada akhir putaran dadu sang pemindai waktu
Ia tiba di langit Paris sebelum jatuh pagi
Dalam perjalanan itu: raganya terus bercakap dengan jiwanya
Maut menjaga jarak seperti penujum yang sabar
Malam adalah bagian yang menyenangkan
Dari serangkaian kesibukan menerima tamu
Mereka menyamar sebagai damar yang melekat pada kain
Kadang beralih rupa rama-rama di taman seluas mata
Menyusup ke dalam sup di mangkuk tembus pandang
Atau sekadar sepat kopi yang kekal di lidah
Seluruh wahyu merasuki sukma
Bertukar tenaga dengan cahaya
Untuk malam-malam berikutnya
Penunjuk jalan bagi pengembara yang belum rehat lewat senja
Ia terus melayang ke barat
Tempat sebagian pengetahuan berpusat
Lambat atau lesat, ia salin sebuah sejarah
Puisi adalah sulingan sunyi dari perasan darah
Jakarta, 2016
Saat-saat yang Tak Gampang
dan Saat-saat yang Tak Lekas Hilang
–Ramdan Malik
Hakikat seorang pejalan bukanlah menghitung langkah
Jejak itu mencatat kehadiranmu
Di rumah-rumah hati, di ranah-ranah sunyi
Di tempat-tempat tak terduga waktu tetap terjaga
Air mata yang mudah merembes itu
puisi tak tertulis, seperti embun yang kalis
Namun buku di rak sanubari menjadi bacaan para malaikat
Pandang matamu tembus ke segala arah:
Deretan rumah putih megah sebagai cadar kemiskinan
Tilas telapak kaki Bapa Ibrahim dalam noktah sejarah
Pesan yang tercantum pada nisan seorang demonstran
Banjir yang senantiasa turut menenggelamkan perasaan
Kekerdilan fatwa yang kehilangan akar sejarah
Cinta yang berulang kali tertampik arus kebencian
Gugur Tahun
Lagu dan syair kesukanmu, keindahan tajam sembilu
Kau membiarkan pintu dan jendela tetap terbuka
Almanak tak pernah berakhir, seperti si bijak yang tak henti
berpikir. Dan helai-helai daun terus berzikir
Di saat-saat yang tak gampang, kita berutang peruntungan
pada ketulusan sahabat, mencoba bertumpu pada iman dan
pengetahuan. “Kepercayaan pada esok dan lusa, aku suka.”
Hanya pada segenap kegelapan cahaya memiliki jati diri. Itulah
saat-saat yang tak lekas hilang.
Jakarta, 2016
Catatan:
“Gugur Tahun” adalah judul lagu Leo Kristi
“Kepercayaan pada esok dan lusa, aku suka” adalah salah satu baris lirik lagu
“Marga, Souvenir Pojok Somba Opu” karya Leo Kristi
Mengenang Bandung dari Jauh
Jalan-jalan basah menuju puncak bukit, hutan kecil,
rimbun daun
Jalan-jalan rindang dengan pohonan yang setia
menjadi payung
Jalan-jalan teranyam rumit, gang-gang dengan
rumah yang rapat
rumah yang rapat
Jalan-jalan yang seperti beku, garis-garis wajah kota
yang tak berubah
Jalan-jalan dengan lalu-lintas sibuk, warna-warni
terhenti, bergeser lambat
Jalan-jalan yang hangat oleh kafe, aroma kopi-krim
suara kenes mojang Priangan
Jalan-jalan sendu dan larut di bawah embun malam,
sinar lampu yang temaram
Jalan-jalan dengan lintasan cepat, waktu dan peristiwa
tumpah-tindih
Jalan-jalan gembur, ladang subur penuh tanaman sayur
Jalan-jalan berhias gelak-tawa anak muda, aroma
keringat mahasiswa
Jalan-jalan dalam denyut rahasia, malam dengan musik
fusion, ciuman berkelebat
Jalan-jalan menukik sunyi pada tebaran kabut, samar
uap jagung rebus
Jalan-jalan berserak aneka rona bunga, ucapan selamat dan
warna perak kematian
Jalan-jalan tak tentu arah, memisah dari mata angin
Jalan-jalan saling bersilang, menembus hatimu, menderu
suara di hatiku, terseret gelombang waktu
Kini membayang dalam genangan air mata
Ketika semua menjadi jauh
Seperti sebuah jarak
Jakarta, 1999
Cinta Randu Alas
Cintaku padamu meniru akar randu alas
Melesak dalam sela batu bumi, mengikat
erat beribu hikayat. Di ranah Sebayu, kurawat
sumur dan tanah gembur
Kuingin anak cucu berkumur kenangan, mineral
yang membangun jiwa mereka subur
Cintaku padamu serupa pucuk ranting randu alas
Mencium ubun-ubun langit, memandang cakrawala
berbatas pantai dan bukit. Laut utara menanggung
lara, lereng Gunung Slamet menuang kasih sayang,
mengalir siang dan malam lewat Kali Gung
Jauh sudah bunyi letupan bedil, berganti
berondong mercon setiap awal Lebaran
Cintaku padamu ibarat batang raksasa randu alas
Tahun demi tahun menghimpun sari perasan
sejarah. Getah yang melahirkan para perantau,
kaum tahan banting, lengan-lengan yang bekerja
Laju permukiman, industri rumahan, tajuk
ranum kesenian: seriang arakan kapuk
dalam tarian angin
Balikpapan-Samarinda, 2014
Avi
– dari penyair yang belajar interior kepada penyair yang
belajar arsitektur
Bagi senja yang sayapnya selebar cakrawala, waktu
adalah bentangan ruang
Tak lebih luas dari hatimu
Namun leluasa untuk secangkir kopi dan percakapan karib
tentang sejumlah kwatrin
dan komposisi piano Johan Sebastian Bach
Di bawah bukit, kota menyapa dengan morse cahaya
Mengingatkan rencana makan malam:
dimsum hangat di cawan tembikar
Angin mengirim salam terakhir koloni burung yang terbang pulang
Menit tak akan mangkir, bahkan ketika kita lupa bersulang
Tangga menuju rumahmu disusun dari bilah-bilah kenangan
Taman ditumbuhi aneka peristiwa, kini berkisah kembali
Riang diwakili kemuning dan cempaka, hampir
menampik melur dan kenanga yang basah air mata
Biarlah cemara yang jangkung dan rimbun soka
menjadi pelindung dari aum serigala
Di credenza, tahun-tahun terhenti, abadi:
Wajah kecilmu,
doa-doa dari tanganmu
senandung dari mulutmu
Jam menjatuhkan detik serupa gerimis, berserak
di lantai foyer, terpantul pada kristal lampu
dan kertas perak pembungkus hadiah
Di bawah rasi Gemini engkau menari
dari ruang ke ruang:
Terakota beranda,
patio tempat patung mengaso,
pantri penuh pastri,
kamar tidur untuk dongeng yang melantur
Tak ada janji sesudah ini, misalnya dengan puisi yang nyeri
Rasa takut melahirkan pertanyaan
: adakah cinta masih mudah diunduh dari reranting yang rapuh?
Masih banyak tempat pakansi untuk mngistirahatkan imajinasi
Negeri muasal korintian atau kapel-kapel ungu
Tanah semai euforbia atau kubah yang selalu dirundung salju
Jakarta, 2016
Lebak Gede, Lukisan Hujan
Telah lewat tengah malam, ketika
hujan turun. Telah lewat ronda malam,
jalanan basah udara penuh embun
Temaram cahaya lampu luntur dalam kabut
Hanya kulihat dari balik kaca:
Kuyup langit menjelang subuh, dan
bercak emas yang jatuh terbawa air
Tuhan menidurkan kalian dalam dingin
rumah papan. Tuhan mengunjungi kalian
dalam mimpi yang transparan
Hanya kulihat dari balik kaca:
Kristal hujan membasuh pohonan, yang
gagal menjadi sebuah hutan
Karena kalian tinggal berdesakan
Telah lewat cahaya bulan, ketika
hujan turun. Banjir di selokan,
seluruh angan-angan
Bandung, 1989
Menisik Sajak Pusaka
Gerimis mempercepat kelam
Dan di ambang malam aku mengakhiri ziarah
Ketika seluruh sajakmu jadi merah, merasuk dalam darah
Di perasaan penghabisan segala melaju
Terus, terus, tak lagi mau menunggu
Cahaya dan kurun waktu bersatu di depan pintu
Aku mengembara di negeri asing
Mencari tanda, mencari makna, isyarat benda-benda
Mungkin tak kan kembali jika itu berarti mati
Dalam sunyi malam ganggang menari
Ditingkah musik gemuruh hati
Aku rindu keadaan sendiri ketika semua tampak sejati
Aku tidak tahu apa nasib waktu
Sesuatu yang Mahatahu membikin hijau atau ungu
Dua puluh tujuh tahunku dirundung kelu
Di Karet, di Karet (daerahku y.a.d), sampai juga deru dingin
Aku berkemas dengan cemas, berpisah dengan puisi
Jiwa yang selalu menemani
Rumahku dari unggun timbun sajak
Bersusun tinggi antara niat dan langkah pasti
Menyentuh langit dan kibaran doa
Aku sekarang api, aku sekarang laut
Membakar perjuangan, menggulung beribu lawan
Tak sudi menyerah untuk kalah
Kau depanku bertudung sutra senja
Tak mungkin kabut menyembunyikan parasmu
Maut yang membiru
Hidup hanya menunda kekalahan
Untuk diulur dari tahun ke tahun
Mmendam cinta di lubuk terdalam
Antara bahagia sekarang dan nanti jurang ternganga
Mungkin titian kata-kata
Menyeberangkan kita saling mendamba
Berjagalah terus di garis batas antara pernyataan dan impian
Sebab tak ada hidup tanpa kekuatan jiwa
Untuk memperabukan seluruh kehendak
Jakarta, 2016
Catatan:
Pada puisi “Menisik Sajak Pusaka”, setiap baris pertama yang dicetak miring diambil dari larik puisi Chairil Anwar yang berbeda-beda (dari 12 puisi)
Taman Laut
– Gratiagusti Chananya Rompas
Jejak bulan samar pada langit biru memar
Di ambang jendela subuh, kukenang suaramu:
Paduan nada manja, kantuk yang memberat, dan
gangguan sinusitis pada hidungmu
Menggubah senandung terindah sepanjang hidupku
“Maaf telah membangunkanmu. Sekarang
memang masih terlampau pagi.
Ada waktu setengah jam untuk tidur kembali.”
Saat matahari merambat pelan, kita sarapan tinutuan
Melekat gurih perkedel ikan nike di semenanjung Wakeke
Angin bertiup ramah memperkenalkan rasa garam
Di pergelangan tanganmu, jarum arloji
mengingatkan waktu menyelam
Bibir dermaga memperlihatkan sepotong paras Venesia
Meluas gelombang agar-agar biru menyentuh cakrawala
Di atas kapal, senyum dan geriap rambutmu
menghias bingkai jendela
Melajulah perahu mengarungi biru lazuardi muda,
biru ultramarine samudra, biru toska Bukit Manado tua,
biru indigo palung tak teraba
Melaju berperahu melupakan rahang hiu
Di atas katamaran, kita mengintai dasar lautan
Terhampar panggung bening tempat ikan-ikan menari
Warna-warni karang terbungkus sulur ganggang:
sebentang istana yang nyaris hilang.
“Aku ingin terapung di atas taman laut. Mengintip
cahaya di ceruk karang dan lumut.
Bercanda dengan ikan-ikan yang tak kenal takut
Abadikan saat jemariku dipagut.”
Tengah hari singgah dan belanja di Pantai Bunaken,
terhirup aroma ikan bakar sepanjang pesisir.
Kita bukan turis yang tekun dan telaten,
memisahkan hasrat dari cinta yang berdesir.
Melajulah perahu kembali ke pelabuhan awal, mengarungi
biru langit matahari siang, biru laut haus terpanggang,
biru gunung berpayung awan, biru palung lembah cendawan
Melaju berperahu pulang ke tanah asal
Sebelum tiba di tepian, kudengar jejak tawamu
memperpanjang suara syahdu
Jakarta, 2008
Sinanggar Tullo
Aku yang tak mahir berenang lebih mencintai air
ketimbang padang pasir. Kutenggelamkan tubuh dalam-dalam
memeluk karang Danau Toba. Tiada arak di sana, tapi aku
mabuk membayangkan jadi seekor bintang. Di dasar langit
hijau tua, berkelip memanggil juru mudi kapal yang bengal.
“Mari santap hidangan ganggang hangat, agar
ia tumbuh kekal dalam lambungmu.”
Memandang gulungan air tersibak
menjadi anak-anak ombak yang jinak
Sejumlah pusaran pergi menyendiri dan mengirim pesan
dari kekasih: putri nelayan yang kesepian
“Sudah kudendangkan sinanggar tullo berulang-ulang,
siang dan malam, menyambut rindu.
Namun yang kuterima melulu pilu.”
Kami sempat membenci deru mesin perahu. Mengingatkan gemuruh
perang melawan pasukan mangmang. Kami pernah sembunyi di
celah bukit terendam lantaran takut mati
Angin mengikis batu gantung
jadi belahan jantung. Putih perih dalam kilatan sinar mentari muda.
“Berhimpun di bahtera ini. Jangkar berakar sudah
ke lembah danau. Tempat memanjat ikan paling renta,
nenek moyang kita semua.”
Samosir-Toba, 2014
Bedugul
Kaki-kaki bukit yang menyelam ke dasar telaga, melahirkan
anak-anak ikan. Pada rambutnya yang bermahkota kabut,
sesekali menyembur gerimis. Keluarga raya wanara menanti
penggemar: kaum pelesiran yang mencairkan pundi tabungan
—dingin meraut kulit
Kelok jalan mengerat bukit seperti pisau alit mengupas limau
Dari tubir tinggi memandang danau bersalin hijau. Kita tak
mengenal karib penghuni di kedung-kedung suwung. Meski
telah mereka ajak saudara kita anjangsana dan berumah di sana
—akar melilit surya
Singaraja, 2011
Shofa dan Briza dalam Komposisi Tengah Hari
Di atas permukaan batu alam yang kasar, Shofa dan Briza
menciptakan kehidupan. Pada lembar dunia yang lain
mereka melahirkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka
menggariskan nasib dengan pikiran, menandai dengan aksara,
menanamkan berbagai perasaan, seperti angin meletakkan
serbuk sari pada rekah putik
Pada jarak yang terjangkau tangan, aku menciptakan dunia bagi
Shofa dan Briza. Mereka bukan merpati yang gemar memainkan
sayap bersenda gurau di teras pegupon. Kuletakkan mereka pada
bentangan pikiran, tanpa ruas tanpa batas, kecuali cahaya dari
matahari yang sama. Dialah benda yang membocorkan rahasia di
antara kami, bahwa tengah hati sedang menghampiri
Aku tak mungkin menduga isi hati Shofa dalam asuhan angin
taman, ketika daun-daun kering luruh ke pangkuan memberinya
inspirasi. Aku tak sanggup mencuri isi kepala Briza yang
terpukau suara dari balik punggungnya. Mereka kini menjadi
bagian dari sebuah taman: serupa patung batu atau serumpun
perdu, mirip fontain yang riang atau bangku beton dengan
sisa remah cokelat, bagai lampu tanam yang bertugas memberi
cahaya dari cekung tanah sehabis senja
Ini tengah hari berangin, waktu aku bebas berangan, sepanjang
aku betul-betul beringin
Jakarta, 2011
Mata Jiwa
– untuk Tiara Widjanarko dan Andhika Sastra
Di bawah tudung langit
Kalian ibarat samudera
Yang mempertemukan dua kutub
Di mata kasih Tuhan
Kalian sepasang insan
Yang saling mengulurkan tangan
Di bawah kanvas pelangi
Kalian memilih Februari
Tempat gerimis dan cahaya menari
Di bawah kesaksian malaikat
Hati kalian saling terikat
Cinta tumbuh serupa hutan lebat
Di bawah senyum rembulan
Kalian menanam rindu di taman
Kasih yang tak berkesudahan
Di balik bilik sunyi
Kalian mengucapkan janji
Untuk menepati dan tidak mengingkari
Di bening mata jiwa
Kalian berendam dalam cinta
Panen raya cerita
Jakarta, 2015
Puisi di Bangku Taman
Hanya yang pergi meninggalkan petisi. Janji yang ditangisi.
Sesudahnya, waktu berlari, sendiri. Putih seperti aster yang
pucat. Dibalut kafan angin barat.
Penghuni baru tak menghapus kisah, justru menambahkan
halaman. Bingkai musim seindah ciuman yang tak direncanakan.
Memperlambat hari. Mematangkan ilusi.
Di luar suara yang memperdebatkan cinta, sepasang merpati
berpaut paruh. Mereka merelakan sebatang bulu sayapnya untuk
menulis puisi. Tentang sentuhan manis dan ucapan getir.
Hujan yang dikira hendak melenyapkan setiap catatan upacara,
di luar dugaan, justru mengekalkan. Pagutan kuat kata-katamu
seperti taring yang menangkap leher pasrahku.
Jakarta, 2011
Interior Senja
Itulah pantai
Dengan batas langit dan kaki bukit
Sebentuk pinggang benua
Terlihat ramping dari angkasa
Alangkah gaduh cuaca
Seperti sisa perang brubuh
Yang bergerak meninggalkan ekuator
Dari bingkai jendela
Tumbuh menara korintian
Membatas warna, membedakan waktu yang tersisih
Dan reda menjelang malam
Bekas hangat bibirmu
Ingin menetap di tengkuk
Tak kudengar ucapan perpisahan
Selain desir langkah yang meninggalkan
Alangkah gaduh perasaan
Sayatan emas yang tercampak di cakrawala
Telah mengirim ujung kerasnya ke jantungku
Meninggalkan bercak merah padam
Itulah senja
Dengan batas langit antara dua waktu
Dan keputusan yang segera
Dilupakan
Jakarta, 1997
Tentang Kurnia Effendi
Kurnia Effendi lahir di Tegal, 20 Oktober 1960. Menulis puisi dan prosa yang terbit pertama di media massa tahun 1978. Lulusan dari FSRD ITB ini pernah bekerja di perusahaan otomotif selama 19 tahun hingga pensiun di 2015. Kini mengabdikan diri pada kegiatan seni budaya: sastra, batik dan seni rupa. Antologi puisinya: Kartunama Putih (1997), Mendaras Cahaya (2012), Senarai Persinggahan (2016). 15 buku yang lain adalah kumpulan cerpen, bunga rampai esai, novel dan memoar.
Catatan Lain
“Pada dasarnya saya menggemari tema cinta, oleh karenanya sangat sedikit puisi yang mengangkat isu politik, bencana, atau sains,” tulis si penyair dalam pengantar yang dijudulinya Appetizer itu. Sebelumnya ia berkata: “Jika saya katakan bahwa selama merasa menjadi penulis saya telah membuat lebih dari 2500 puisi, terasa berlebihan. Saya pun tidak menghitungnya dengan teliti, apalagi setelah seluruh dokumentasi digital lenyap dicuri. Mungkin yang paling monumental adalah janji menulis 1000 puisi dalam 6 bulan yang saya lakoni di tahun 1996 (sejak 30 Juli hingga 31 Desember). Penerima perjanjian maupun penyimpan puisi-puisi saya itu hingga kini menjadi sahabat, yakni Ana Mustamin. Hal kedua adalah tradisi menulis puisi berseri setiap Ramadan yang berlangsung sejak 1987 hingga 2016, dan semoga berlanjut. Itu semacam ritual ibadah puisi di bulan puasa,” tulisnya (hlm. 7).
Halaman persembahan (hlm.11) berisi tulisan ini: Dan, wahai, tak sama jumlah bulu matamu/Antara yang kanan dan kiri. Sampul belakang berisi kutipan pengantar penyair dari 2 paragraf yang berbeda. Begitu.